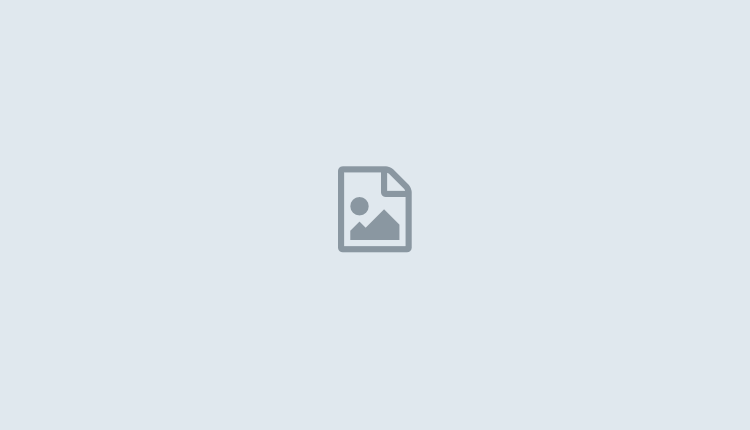Mahasiswa Anggap Saya Raja Tega dan Kambing Hitam
SEMESTER genap tahun akademik 2015/2016 dimulai. Aha…, banyak mahasiswa yang menghindar masuk ke kelas mata kuliah yang saya ajarkan. Mereka menganggap saya dosen killer.
Belum lagi semester genap dimulai, belasan mahasiswa menemui rekan dosen di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Sang dosen selama ini mendampingi mahasiswa komunikasi-jurnalistik yang sedang mengikuti kuliah kerja lapangan (KKL) atau magang. Semester lalu, saya juga menangani mata kuliah ini. Hasilnya, delapan dari 15 mahasiswa yang berada di bawah bimbingan saya tidak lulus.
Teman dosen bercerita bahwa belasan mahasiswa yang menemuinya menyatakan tidak ingin saya berada di kelas mereka. Alasannya, ya itu tadi, saya dianggap sebagai dosen killer, terlalu keras dan menerapkan standar penilaian terlalu tinggi.
Para mahasiswa tadi bolehlah lega sebab pada semester genap ini saya tidak mendapat tugas untuk mendampingi mereka dalam mata kuliah KKL. Dengan begitu, mereka tidak akan menerima tugas mingguan dari saya untuk membuat karya jurnalistik yang hasilnya kerap saya corat coret lantaran kalimat yang ditulis para mahasiswa tidak logis, tidak akurat dan tidak jelas.
Maaf, para mahasiswa, saya “keras” kepada Anda bukan tanpa sebab. Saya “reseh” kepada Anda semata-mata agar Anda profesional saat menekuni dunia jurnalistik yang menuntut para pelakunya disiplin, terampil, akurat dan militan.
Dalam membimbing Anda para mahasiswa, saya menganut prinsip “lebih baik berkeringat-keringat di masa damai daripada berdarah-darah di saat perang.” Konkretnya, lebih baik Anda digembleng secara keras selagi di kampus daripada mengalami “penderitaan” saat Anda bekerja di dunia jurnalistik.
Saya menuntut mahasiswa agar teliti dan profesional, sebab saya kerap mendengar keluhan dari perusahaan media massa, tempat di mana mahasiswa magang atau praktik kerja, bahwa para mahasiswa yang ber-KKL tidak berdisiplin dan enggan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan redaktur. Intinya, para mahasiswa malas, tidak bersemangat dan tidak militan terjun ke dunia jurnalistik.
Salahkah saya dalam menggembleng para mahasiswa? Killer-kah saya? Lebaykah saya dalam mendidik dan mendampingi mahasiswa? Seperti apa sebenarnya penilaian mahasiswa atas cara saya mengajar?
Pendapat Natalia Simanjuntak, salah seorang mahasiswa saya di Universitas Esa Unggul, layak saya jadikan pegangan. Di kampus itu saya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia jurnalistik (BIJ) dan jurnalistik-stylistik.
Dalam blognya, Natalia menulis: “Tidak terasa enam bulan telah berlalu. Masih lekat dalam ingatan campur aduknya perasaan kami saat mengikuti kelas keramat ini di hari pertama. Mengapa disebut keramat? Karena mata kuliah di semester sebelumnya, Bahasa Indonesia Jurnalistik, dengan dosen yang sama, telah sukses menggugurkan banyak mahasiswa dan memaksa mereka untuk mengulang di tahun berikutnya. Oleh karenanya, banyak mahasiswa yang menjadi “alergi” terhadap mata kuliah ini, lebih-lebih terhadap dosen pengajarnya.”
Gantyo Koespradono, begitu tulis Natalia, dosen yang paling kami takuti karena tidak segan-segan memberikan nilai C, D, bahkan E untuk mahasiswanya. “Yah, Pak Gantyo lagi. Siap-siap ngulang lagi ini mah!” keluh salah satu mahasiswa ketika mengetahui bahwa jurnalistik stylistik diajar oleh Pak Gan.
Namun ternyata, masih menurut Natalia dalam blognya, bayangan buruk itu perlahan sirna. “Kami mulai merasa nyaman. Tidak lagi tertekan seperti dulu saat mempelajari BIJ. Entah mengapa.”
Natalia menyebut, metode mengajar yang saya gunakan lebih santai, banyak tertawa, dan berguyon. “Kami pun turut terbawa suasana tersebut, kami tidak segan-segan bertanya dan mengemukakan pendapat. Tidak ada lagi ketakutan, melainkan perasaan hangat dan kekeluargaan.”
Di akhir tulisannya, Natalia bertanya, apakah di akhir semester tiga ini saya masih takut terhadap mata kuliah stylistik dan jurnalistik? “Tidak! Pasalnya, mata kuliah “keramat” ini justru semakin menggembleng semangat saya untuk semakin rajin berlatih menulis.” Penasaran dengan tulisan Natalia, silakan klik di sini (saya sarankan Anda buka setelah selesai membaca catatan saya ini).
Dalam soal ujian akhir semester (UAS) ganjil yang lalu, saya minta kepada para mahasiswa agar membuat karya jurnalistik berstylistik tentang mata kuliah tersebut. Saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa agar menulis topik tersebut dari berbagai sudut pandang.
Menjawab soal UAS tersebut, Sumarni, salah seorang mahasiswa, mengungkapkan bahwa mahasiswa komunikasi universitas tersebut menyebut saya sebagai “si raja tega” karena saya pernah memberikan nilai telor (nol) kepada mahasiswa.
Meskipun banyak mahasiswa yang “down” setelah melihat nilai yang diperoleh, menurut Sumarni, nyatanya nilai itu menjadi motivasi bagi mahasiswa. Mahasiswa di bawah bimbingannya, tulis mahasiswa berjilbab ini, akan mengetahui perkembangan belajarnya melalui nilai-nilai yang diberikan Gantyo, meskipun hasilnya menyakitkan.
Sumarni menulis, selain gelar “raja tega”, Gantyo termasuk dosen yang sangat teliti. “Keteliannya patut diacungi jempol. Semua hasil tugas mahasiswa dikoreksi dengan detil, baik itu menyangkut typo, penulisan kalimat, kata-kata aneh, dan sebagainya. Mahasiswa akhirnya bisa belajar dari kesalahan yang dilakukan.”
Rizki Amalia, mahasiswa lain, menulis jawaban UAS seperti ini: “Dosennya tidak kaku dalam mengajarkan saya dan teman-teman. Kami seperti sedang sharing, bukan melakukan ritual perkuliahan. Saya bertanya-tanya mengapa ada saja mahasiswa yang memberikan julukan dosen reseh padanya. Mungkin dia kurang menikmati mata kuliahnya, sehingga dosen dijadikan kambing hitam. Dosennya memang disiplin sih, tapi semua itu dilakukan demi kebaikan kita, bukan?”
Kamsilah mengungkapkan disiplin waktu menjadi ciri khas dosen satu ini, ia mulai memberikan kuliah tepat pukul 08.00. “Perasaan berkecamuk dalam diri saya. Bukan tanpa alasan, sebab dosen ini dikenal dengan julukan pelit dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Saya pernah mendapat nilai yang jauh memenuhi standar,” tulis mahasiswa ini.
Siti Nahdiatul Murtaza, mahasiswa yang pernah praktik di Media Indonesia, mengaku saya sebagai sosok yang menakutkan, tapi juga membuatnya penasaran. Ia kaget dan terheran-heran karena saya memberikan nilai 72 untuk mata kuliah yang saya ajarkan. “Sampai-sampai saya protes sama Pak Gantyo, mengapa dia memberi nilai saya tinggi. Sejak itu gue nggak takut lagi dan gue optimis bisa dapat nilai A untuk mata kuliah jurnalistik stylistik,” tulisnya.
Yohanes Irawan, rekan Siti, mengungkapkan kesan-kesannya seperti ini: “Berbekal pengetahuan dan segudang pengalamannya, ia mengajar dengan teknik sersan (serius tapi santai). Satu pengalaman langka yang belum tentu didapatkan mahasiswa di mana pun. Riuh tawa, celotehan jenaka mencuat di sela-sela materi yang disampaikan.”
Cara mengajar seperti itu, diakui Irawan, membangkitkan semangatnya untuk menghasilkan tulisan yang berkarakter. “Bagi saya ini adalah permainan yang mengasyikkan,” ungkap Irawan.
Terserahlah jika Anda menyimpulkan apa yang saya tuangkan di atas sebagai bentuk aksi narsis dari saya. Namun, yang pasti, saya telah melecut dengan keras mahasiswa-mahasiswa di atas. Saya juga kerap nyinyir kepada mereka dan pernah memberikan nilai minor atas tugas yang saya berikan kepada mereka.
Apa yang saya lakukan kepada mereka tidak sia-sia, sebab dalam UAS tempo hari, mereka mendapat nilai A-B. []