KESAKSIAN SEORANG MANTAN PELACUR
Catatan Gantyo tentang kisah seorang mantan pelacur:
AKU lahir di Jakarta 24 April 1959. Sejak kanak-kanak, aku tidak tahu ke mana aku akan arahkan hidupku. Yang aku tahu, ayahku bernama Lim Poe Ian yang kemudian bernama Indonesia menjadi Hariadi. Sedangkan ibuku bernama Ak Kian (Siti Mulyani).
Aku adalah anak kedua dari enam bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki bernama Harianto, sekarang tinggal di Sukabumi sebagai pengangguran. Aku adalah anak kedua. Orang tuaku memberikan namaku Hwe Tjoe. Sedangkan nama Indonesiaku adalah Hariyati. Namun sampai sekarang aku biasa dipanggil Icu, plesetan dari nama asliku, Hwe Tjoe.
Anak ketiga Papa juga laki-laki diberi nama Mulyono; pekerjaannya sekarang adalah sopir pribadi. Anak keempat bernama Jayanto. Tidak sesuai dengan namanya yang mengandung unsur “jaya”, adikku laki-laki ini, hidupnya tidak pernah berjaya, setidaknya menurut ukuranku. Belum lama ini dia meninggal dunia dengan pekerjaan terakhir sebagai pemulung. Banyak memang yang tidak percaya, mengapa kehidupannya, juga kehidupan kami sedrastis itu, sebab banyak orang yang menganggap keluarga keturunan China umumnya kaya-kaya.
Anak kelima Papa juga seorang laki-laki bernama Mulyadi. Sekarang tinggal di Cisarua, Jawa Barat sebagai tukang ojek yang sering mengangkut sayur-sayuran ke pasar.
Anak perempuan kedua setelah aku adalah Mulyaningsih. Adikku yang biasa dipanggil Merry ini adalah anak keenam Papa-Mama. Dia seorang ibu rumah tangga yang pengalaman hidupnya juga sangat “kaya” dan unik seperti halnya aku; dan aku pernah menjadi duri dalam daging perjalanan hidupnya.
Selain mereka, di rumah kami juga ada nenek, ibunda Ibu. Kami panggil nenek dengan sebutan Emak. Dia sangat baik dan peduli kepada cucu-cucunya, terutama aku. Emak sering mengajak aku bermain bersama, terutama jual-jualan. Emak dan aku dalam permainan itu seolah-olah jadi pedagang kaki lima. Senang sekali jika nenek mengajakku bermain seperti itu.
Buatku, Emak adalah segalanya. Kasih sayangnya melebihi kasih sayang yang diberikan Ibu kepadaku. Menginjak remaja, saya baru menyadari, “kasih sayang” yang diberikan Ibu kepadaku ada pamrihnya, bahkan bermotif ada udang di balik batu. Aku tidak habis mengerti, mengapa Ibu menjadikan aku seperti itu.
Di samping nenek, di rumah Kebon Kacang, juga ada kakak sepupuku bernama Tan Oek In. Kami sering memanggilnya dengan Ambon. Kami memanggilnya seperti itu, sebab kakak sepupuku ini berkulit gelap dan berambut agak keriting, mirip orang Ambon, meskipun dia Tionghoa asli yang biasanya berkulit kuning dan berambut lurus.
Usiaku berbeda dua tahun dengan Ambon. Dia lebih tua. Dalam usianya yang masih muda, dia sudah bisa cari uang sendiri sebagai tukang dorong sepeda motor yang akan melintas di rel kereta api yang melintas di Jl Gunung Sahari, seberang kompleks Akademi Ilmu Pelayaran (AIP). Di tepi Jl Gunung Sahari, melintas Sungai Ciliwung. Setelah rumah kami di Kebon Kacang dibongkar, kami pindah di Jembatan Baru, Gunung Sahari, Ancol. Ambon sering memberi uang kepadaku.
Meskipun aku punya seorang kakak dan tiga adik laki-laki, aku lebih akrab dengan Ambon. Dia sangat sayang kepada diriku, dan selalu jadi pelindung jika aku punya masalah atau diganggu oleh kakak dan adik-adikku.
Adik Mama yang bernama Tjwa Heng Hok dan Tjwa Kim Eng juga tinggal bersama dengan kami. Di mataku, Om Tjwa dan Om Tjwa Kim Eng orangnya baik. Saat usiaku 5-6 tahun, keduanya sering mengajakku jalan-jalan. Senang sekali aku diperlakukan seperti ini, jalan-jalan dengan om.
Kalau ditanya, tipe seperti apakah keluargaku, aku tidak tahu. Hubungan antara Papa dan Mama biasa-biasa saja. Apa pekerjaan Papa, aku juga tidak tahu. Yang pasti, Papa sering meninggalkan kami dan Ibu. Dia sering bepergian ke luar negeri. Katanya ke Singapura untuk urusan dagang. Tapi dagang apa, aku tidak tahu.
Saat di Kebon Kacang, Papa punya mobil Mercedes. Itu berarti Papa lumayan kaya. Rumah kami di sini juga besar. Perawakan Papa lumayan tinggi. Dia tidak berbahasa dan baca tulis Indonesia. Yang dia kuasai hanya bahasa Mandarin. Jika dipaksakan berbahasa Indonesia, logatnya adalah logat Mandarin. Kalau di Jawa Tengah, model orang Tionghoa seperti Papa inilah yang sering disebut sebagai China singkek atau China totok.
Orang China totok sering dikenal pelit. Sepertinya Papa juga begitu. Meskipun punya banyak uang, Ibu tidak pernah menyimpan uang untuk kami anak-anaknya. Tak satu pun anak-anaknya disekolahkan. Benar, kami hingga dewasa tidak mengenal baca tulis.
Meskipun Hariadi adalah ayah kandung kami, aku tidak pernah mengenalnya sebagai ayah. Aku lebih dekat dengan nenek, om dan saudara sepupuku daripada Papa. Kehadiran Papa, baru kami rasakan manakala di antara kami melakukan kesalahan.
Papa kerap menghukum kami dengan cara mengurung kami di kamar mandi. Rumah model tahun 1960-an, kamar mandi dan WC-nya terletak terpisah di luar bangunan utama. Jika Papa datang dan mengetahui kami sedang nakal, maka yang ada di kepalaku adalah ruang kamar mandi yang menakutkan.
Di mataku, Papa adalah sosok yang sangat menakutkan. Suatu hari, dia pernah menghukum Ambon dengan cara menempelkan potongan besi beton yang telah dipanaskan ke pantat Ambon, padahal Ambon tidak berbuat apa-apa.
Papa menghukum Ambon seperti itu, hanya gara-gara aku iseng membuat laporan palsu ke Papa bahwa Ambon baru saja menjual anusnya ke anak-anak Tanah Abang untuk disodomi. “Pa, pa … lihat tuh, Ambon habis jual bo’olnya ke anak-anak,” kataku iseng mencoba minta perhatian Papa.
Aku berkata seperti itu kepada Papa setelah aku diberi uang oleh Ambon. Pikirku iseng, jangan-jangan uang itu hasil ulah Ambon mengomersialkan bagian tubuh yang ada di pantatnya.
Kehidupan di kawasan Tanah Abang memang liar. Ambon, kakak dan adik laki-lakiku pernah disodomi oleh anak-anak preman di kawasan ini. Karena kurang mendapat perhatian dari orang tua, kami memang sudah akrab dengan peristiwa dan istilah-istilah seks murahan yang sebenarnya belum layak kami ketahui, apalagi kami alami.
Sampai sekarang aku juga sulit melupakan saat Papa menghukumku di saat mengetahui aku berbuat nakal. Papa lalu memelukku dan meletakkan kepalaku di lengannya. Diam-diam Papa menyiapkan gunting dan memotong rambutku di saat aku lengah. Aku benci dan dendam sekali kepada Papa dengan kelakuannya. Setelah itu aku menangis sejadi-jadinya. Papa semakin berang.
Diperlakukan seperti itu, Ibu praktis tidak pernah membelaku, sebab diam-diam Ibu melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak layak kami ketahui. Oleh sebab itulah di rumah, Ibu sering mengurung kami di dalam kamar.
Kami sering melihat Mama keluar pada malam hari, bahkan sering pula beberapa hari Mama tidak pulang dan meninggalkan kami anak-anaknya. Di rumah, kami ibarat anak ayam kehilangan induk. Aku baru mereka-reka apa yang Mama lakukan setelah suatu kali aku diajak dengan Om Tjwa Kim Eng ke sebuah rumah di Jl Kebon Jeruk XVI, Mangga Besar, Jakarta Barat.
Seorang laki-laki di sana berkata kepadaku: “Mamamu kok nggak datang ke sini?”
Mama nggak datang ke sini? Tempat apa ini, pikirku. Belakangan aku baru tahu, ini ternyata rumah bordil dan laki-laki yang berkata seperti itu seorang germo. Tapi pada saat itu, aku tidak tahu apa fungsi rumah bordil; begitu pula Mama ke rumah ini dalam rangka apa.
Tahun 1967 usiaku 8 tahun. Pemerintah Orde Baru baru saja terbentuk setelah pemerintahan Soekarno jatuh. Gubernur Jakarta waktu itu adalah Ali Sadikin. Jakarta sedang giat-giatnya membangun. Banyak rumah yang digusur, termasuk rumah kami di Kebon Kacang. Aku tidak tahu bagaimana prosesnya, dapat ganti rugi atau tidak.
Sebagai seorang bocah, yang kuingat, kami pindah rumah di Jembatan Baru, Jl Gunung Sahari, Ancol. Belakangan aku tahu, ini bukan rumah sendiri, tapi rumah pinjaman dari teman Papa, orang Bugis.
Di rumah yang terbuat dari papan inilah hidup kami benar-benar berubah semakin tidak menentu. Kami tetap tidak disekolahkan oleh orang tua kami padahal usia kami sudah memenuhi syarat untuk bersekolah.
Sejak kami tinggal di rumah ini, Papa semakin jarang pulang, begitu pula ibu. Untuk mendapatkan uang jajan, sepupuku Ambon hampir setiap hari berkeliaran di Jl Gunung Sahari dekat rel kereta api. Dia menjual jasa mendorong pengendara sepeda motor yang mengalami kesulitan saat akan melintas real kereta api setelah berhenti menunggu kereta api lewat. Waktu itu, tonjolan rel kereta api lumayan tinggi dari badan jalan, sehingga menyulitkan sepeda motor melintas. Dari sinilah Ambon mencari nafkah dan sebagian uang yang diperolehnya diberikan kepadaku.
Ingin punya uang sendiri, aku juga membantu cuci-cuci piring di sebuah rumah makan Padang yang lokasinya tidak jauh dari rumah kami. Pada saat itu aku diupah Rp 200 per bulan. Tapi upah ini pun sering tidak aku terima, karena ditahan oleh majikan.
Saat usiaku 11 tahun, aku sudah mengenal dan semakin tahu betapa pentingnya nilai uang. Sebagai seorang bocah, aku juga ingin hidup enak seperti teman-teman sebayaku.
Tapi aku tidak berdaya hingga suatu hari Mama berkata kepadaku: “Kalau kamu mau hidup enak dan punya barang mewah, ikut saja Mama.”
Ikut Mama? Ke mana? Itulah pertanyaan yang ada di kepalaku. Tergiur omongan Mama, aku pun menurut apa yang diinginkan Mama. Aku ikut Mama. Maka suatu hari dengan berjalan kaki, aku dan Mama ke Pantai Bina Ria, Ancol.
Jam saat itu menunjukkan pukul 11.00. Kami pun menuju Pantai Bina Ria yang jaraknya tidak sampai 4 km dari rumah kami. Waktu itu Bina Ria masih gersang. Belum banyak bangunan kecuali Copacabana yang waktu itu dikenal sebagai tempat untuk bersantai. Di sini ada tempat judi, seperti jackpot, ada pula bowling. Tidak jauh dari situ ada sebuah motel. Aku tidak tahu apa nama motel tersebut. Yang aku ingat lokasi motel ini dekat dengan kuburan Belanda.
Setibanya di Bina Ria, Mama mengajakku ke pantai yang berpasir putih. Aku asyik bermain pasir dan membasahi kakiku dengan air laut. Aku ditinggalkan sendirian. Aku melihat Mama menuju ke motel.
Tidak sampai setengah jam, Mama keluar dan menemuiku. Mama kemudian menyarankan aku agar minum pil dengan alasan agar tidak masuk angin. Tanpa perasaan apa-apa, aku pun minum pil pemberian Mama.
Tidak lama setelah itu, kantuk menyerangku. lalu tak sadarkan diri. Begitu tersadar, aku sudah berada di atas ranjang kamar motel. Kancing bajuku tak beraturan, masuk ke lobang tidak sesuai tempatnya. Vaginaku terasa sakit dan mengeluarkan darah.
“Ma, habis ngapain aku di sini,” aku bertanya ke Mama.
“Sudah, nggak usah tanya-tanya. Nanti Mama jelasin di rumah.”
Aku coba bertanya lagi. Bukan jawaban yang kuperoleh, tapi tamparan. Tamparan Mama lumayan kencang. Aku menangis.
Setibanya di rumah, kembali aku bertanya kepada Mama tentang peristiwa yang aku alami, juga tentang darah yang keluar dari vaginaku. Mama menjelaskan bahwa darah di vaginaku adalah menstruasi pertamaku.
Setelah itu, Mama memberiku sebuah kalung emas, dan belakangan warna emasnya luntur. Sejak itu aku akhirnya sadar bahwa Mama telah menjual keperawananku kepada seorang laki-laki yang usianya melampaui jauh usiaku yang saat itu 11 tahun!***

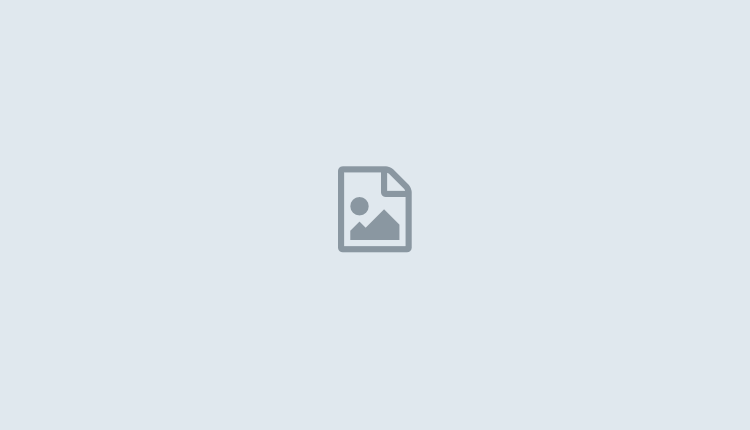
Ya Tuhan … tragis sekali hidup ini. Adakah ini bagian dari ketidakdilan. Mau mengadu kemana?
Siapa yang akan membela ..
Izin ya, kisah ini kami bacain di program taruna cinta radio kami, sebuah cerita yang mengharukan, bikin cerita yang lebih tragis ya… thanks
Halo Radio Taruna
Silakan jika mau dikutip untuk disiarkan di radio.